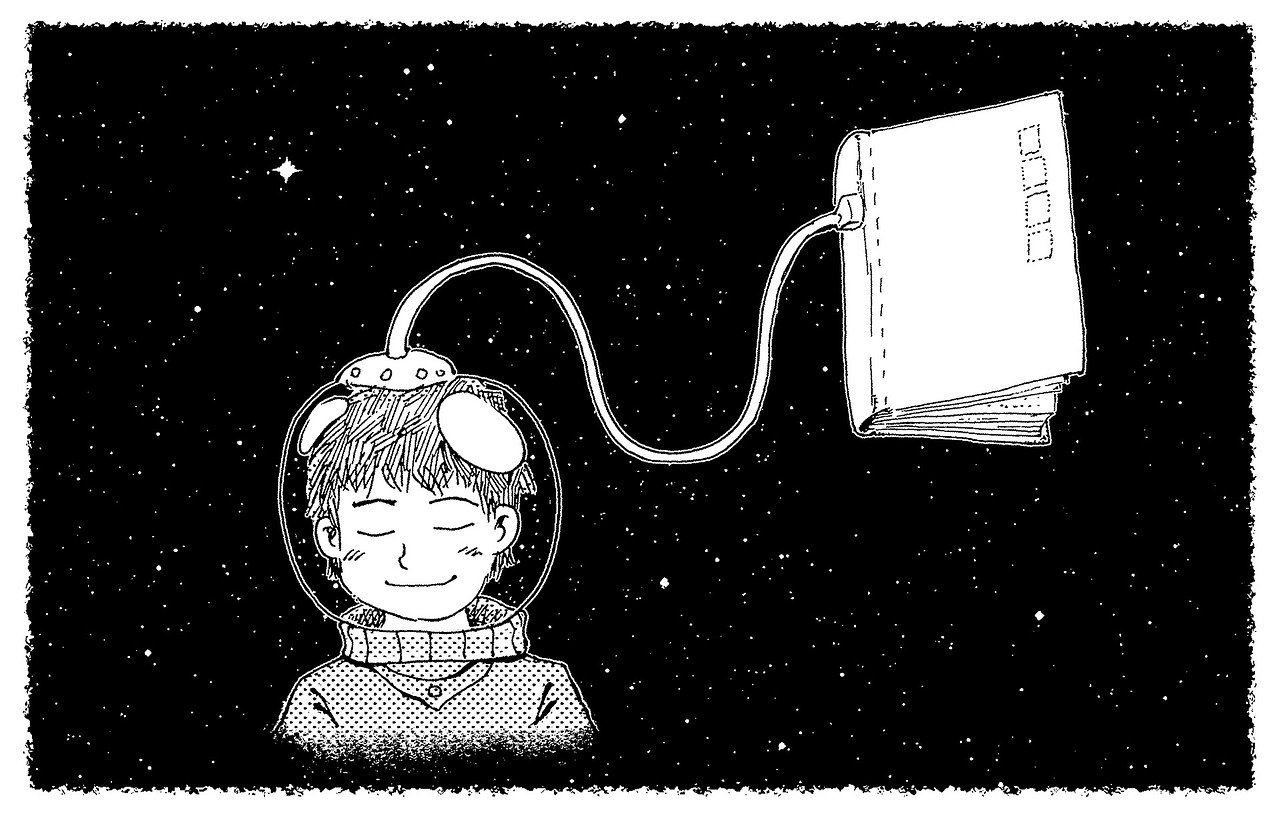Buku Sastra Bukan Sekadar Kliping Karya
Pada suatu kesempatan, saya bertemu dua kawan penyair di salah satu pojok di Pamulang, Tangerang Selatan. Salah seorang di antaranya bertanya: Apakah ada buku Abang yang terbit tahun ini? Saya terdiam sejenak, lalu berkata: “Saya belum bisa menjawab untuk apa saya menerbitkan buku baru?”
Itu bukan jawaban bercanda, tapi sangat serius. Alasannya, pertama, lazimnya yang banyak dilakukan penyair dan penulis cerpen di Indonesia adalah menerbitkan atau membukukan membukukan karya-karya yang pernah dimuat di media.
Jadi, sesungguhnya yang dia lakukan bukan menerbitkan buku, tapi membuat kliping karya dalam bentuk buku.
Boleh juga dikatakan mendokumentasikan karya dalam bentuk buku. Sebab, umumnya karya yang sudah dimuat di media akan dengan mudah dibaca di ruang maya (internet). Maka menjadi masuk akal buku-buku kumpulan puisi dan cerpen diterbitkan itu tidak dibeli orang. Sebab, tidak ada alasan kuat untuk membelinya, wong itu sudah mereka sudah membacanya.
Kedua, jika tidak ada yang membeli, untuk apa saya repot-repot membukukan atau menerbitkan karya dalam bentuk buku. Jika ingin dibuat klipingnya cukup dalam bentuk digital saja (ebook) dan bisa dengan mudah pula dibagikan gratis kepada pembaca yang ingin memiliknya. Toh, banyak penyair pada akhirnya juga membagi-bagikan gratis buku-bukunya.
Keempat, menerbitkan buku mungkin akan saya lakukan untuk karya-karya yang belum pernah dimuat di media. Ini sedang saya kerjakan pelan-pelan. Saya tidak tahu kapan selesainya. Itu pun tidak menjamin buku itu akan dibeli pula. Tapi setidaknya, saya tidak menjual “karya basi” kepada pembaca. Yang saya jual benar-benar karya belum pernah mereka baca.
Maka itu saya untuk sementara menahan diri untuk tidak mengirim karya-karya calon buku itu ke media. Saya merasa tidak perlu mengejar produktivitas atau banyak-banyakan dimuat di media. Tidak ada yang saya kejar. Saya kini hanya ingin membuat puisi (dan sesekali prosa) dengan riang-gembira, dan nanti (saya berharap) yang membacanya pun bahagia.
Saya makin menyadari bahwa menulis puisi itu bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk orang lain. Maka itu saya harus bernegosiasi dengan ego, bahkan kesombongan, yang menempatkan diri sangat jauh dari pembaca. Saya harus mendekontruksi sakralitas hingga batas-batas (antara penulis dan pembaca) runtuh, dan menjadi setara. Bahkan membangun cara pandang baru dalam melihat karya.
Sering kali sebagian penulis menempatkan diri seolah lebih tinggi dari pembaca. Sehingga, seolah-olah, apa yang disuguhkan penulis, akan langsung dilahap oleh pembaca. Padahal, pembaca punya cara berpikir sendiri. Mereka hanya mau membaca sesuatu yang belum pernah mereka baca, atau sesuatu yang menjadi perhatian mereka, atau pula hal-ihwal yang sedang menjadi pembicaraan dalam masyarakat.
Namun karena (sebagian) penulis merasa “di atas” pembaca, maka mereka merasa bisa mendikte pembaca dengan cara berpikir mereka. Hemat saya, inilah salah satunya yang membuat buku-buku sastra tidak “sampai” kepada mereka. Dalam arti, meskipun mereka tahu ada buku itu, tapi mereka merasa berjarak dengannya. Tak lain, karena jarak itu diciptakan oleh penulis itu sendiri dengan halusinasinya sendiri. Akibatnya, tidak ada titik temu antara penulis dan pembaca.
Tentu saja penulis tidak harus mengikuti kemauan pembaca alias selera pasar. Tapi paling tidak, janganlah menyuguhkan “tulisan basi” kepada mereka. Jadi buku bukanlah kliping karya. Tapi buku harus hadir sebagai karya baru dengan menyajikan sesuatu yang belum pernah mereka baca.
MUSTAFA ISMAIL, penulis sastra dan pegiat budaya.